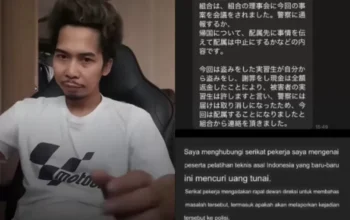BarataNews.id, Jakarta – Pemerintah tengah menghadapi krisis pasokan dan harga beras nasional yang semakin memanas. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap bahwa sekitar 80 persen beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang beredar di pasar adalah hasil oplosan.
Dalam konferensi pers pada Senin (30/6/2025), Amran menyebut bahwa para distributor mengoplos beras SPHP menjadi beras premium, lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi. Dari estimasi total distribusi 1,4 juta ton beras SPHP, sebanyak 1 juta ton diduga telah dioplos. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2 triliun per tahun akibat praktik tersebut.
Polisi telah memanggil tujuh perusahaan produsen beras terkait dugaan penyimpangan ini sebagai bagian dari langkah penyelidikan. Pemerintah pun panik dan mulai dikritik publik karena dinilai gagal mengontrol distribusi dan kualitas beras bersubsidi.
Jejak Lama Beras Oplosan: Kembali ke Tahun 1968
Beras oplosan sebenarnya bukan fenomena baru dalam sejarah Indonesia. Pada 1968, Indonesia juga menghadapi krisis pangan akibat kekeringan global dan ketergantungan pada impor. Pemerintah Orde Baru yang saat itu masih berusia muda di bawah Presiden Soeharto, menghadapi tekanan berat karena keterbatasan cadangan beras dalam negeri.
Di tengah keterbatasan, muncullah inovasi pangan bernama “Tekad”, singkatan dari tela (ubi), kacang, dan djagung. Produk ini merupakan beras oplosan sintetis yang dibuat menyerupai beras sungguhan melalui proses penggilingan dan pencetakan.
Meski diklaim sebagai alternatif nasi, Tekad sejatinya bukan inisiatif langsung pemerintah. Inovasi tersebut berasal dari perusahaan Mantrust, Inc., yang menerima dana kredit pemerintah senilai Rp4,1 miliar untuk membangun tiga pabrik di Jawa.
Dari Alternatif Hingga Gagal di Pasar
Pemerintah menganggap Tekad sebagai substitusi beras untuk menjaga ketahanan pangan. Pabriknya beroperasi di Bandung dan Yogyakarta, dengan kapasitas produksi mencapai 9,6 ton per hari.
Presiden Soeharto bahkan menyampaikan dalam pidato kenegaraan bahwa beras Tekad memiliki kedudukan setara dengan terigu dan bulgur. Target penyediaan pangan pada 1968 mencakup 600 ribu ton pembelian dalam negeri, 600 ribu ton impor, dan 300 ribu ton sisa stok tahun sebelumnya.
Namun, realitas di lapangan tidak sesuai harapan. Harga beras Tekad terlalu mahal tanpa subsidi. Pemerintah kesulitan memberikan dukungan anggaran secara terus-menerus, sehingga produk tersebut tidak mampu bersaing di pasar bebas.
Sebagian masyarakat malah memanfaatkan Tekad untuk membuat camilan atau kue. Gagal menjadi pengganti nasi, beras oplosan Tekad akhirnya menghilang dari pasaran dalam waktu singkat.
Refleksi Krisis Saat Ini
Kondisi krisis beras saat ini membuat sejumlah pengamat menilai pemerintah tengah mengulang pendekatan darurat yang serupa dengan masa lalu. Dengan lemahnya pengawasan di lapangan dan praktik curang oleh pihak distribusi, publik mempertanyakan efektivitas kebijakan pangan nasional saat ini.
Apakah pemerintah akan belajar dari kegagalan masa lalu, atau kembali jatuh pada solusi-solusi instan yang terbukti tidak bertahan lama?